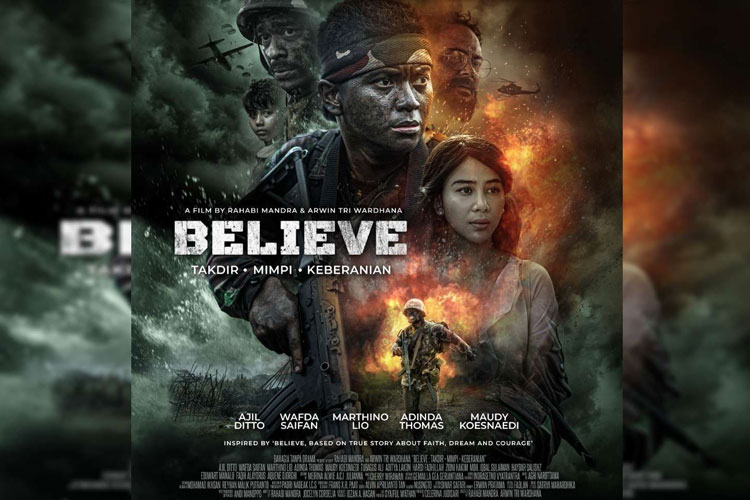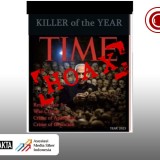TIMES KALSEL, JAKARTA – Setiap siang, jutaan anak sekolah di Indonesia menerima kotak makan siang dari negara. Di balik senyum mereka, tersembunyi keyakinan bahwa negara hadir, memberi asupan gizi agar mereka tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya. Namun di balik gambaran indah itu, sebuah laporan dari Transparency International Indonesia (TII) menyibak sisi lain yang nyaris luput dari sorotan publik—bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyimpan potensi korupsi yang tidak hanya membahayakan anggaran, tetapi juga masa depan bangsa.
Melalui pendekatan Corruption Risk Assessment (CRA), TII membedah program MBG dari hulu ke hilir. Hasilnya mengejutkan: program yang seharusnya menjadi penopang gizi nasional ini ternyata rawan disusupi praktik-praktik koruptif akibat lemahnya tata kelola dan pengawasan.
“Program MBG tampak menjanjikan di atas kertas, namun gagal memenuhi prasyarat tata kelola yang sehat,” tulis TII dalam laporan yang dirilis pada Selasa, 1 Juli 2025.
Angka Besar, Aturan Tak Terlihat
MBG bukan program kecil. Dengan estimasi anggaran sebesar Rp400 triliun dan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta jiwa, ini adalah salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun justru pada skala inilah risiko menjadi sangat nyata. Dalam laporannya, TII menyebut bahwa hingga pertengahan 2025, pelaksanaan program masih belum ditopang oleh Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum. Operasional MBG hanya berjalan dengan petunjuk teknis internal yang sifatnya sementara dan tidak mengikat lintas lembaga.
Tanpa kompas regulasi yang kokoh, koordinasi antar instansi menjadi lemah, dan pengambilan keputusan strategis rentan disusupi kepentingan politik. Akibatnya, kebijakan yang semestinya berpihak pada masyarakat, justru menjadi alat konsolidasi kekuasaan.
Konflik Kepentingan: Ketika Pengelola Terlalu Dekat dengan Penguasa
Salah satu temuan paling mengganggu dari kajian TII adalah soal konflik kepentingan dalam penunjukan mitra pelaksana program. Banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk tanpa proses seleksi terbuka dan transparan. Beberapa bahkan memiliki afiliasi langsung dengan partai politik, institusi militer, atau aparat keamanan. Dalam sejumlah kasus, keterlibatan pihak-pihak tersebut melampaui batas fungsi profesional dan masuk ke ranah eksekusi teknis, seperti distribusi makanan ke sekolah.
Salah satu catatan paling mencolok adalah ditemukannya personel polisi lalu lintas yang ikut dalam penyaluran bantuan pangan. Peran yang tidak relevan secara institusional ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa aparat penegak hukum ditempatkan dalam skema distribusi makanan bergizi?
“Hal ini menciptakan akses preferensial yang merusak prinsip meritokrasi dan netralitas layanan publik,” demikian kutipan laporan tersebut.
Pengadaan Barang dan Jasa: Lubang Lama yang Tak Pernah Ditambal
Risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) sudah lama menjadi titik lemah dalam banyak program pemerintah, dan MBG bukan pengecualian. TII menemukan bahwa proses PBJ dalam program ini kerap dilakukan tanpa dokumentasi terbuka. Tidak ada sistem pengawasan berbasis data yang dapat diakses publik, dan tidak ada mekanisme audit independen yang melibatkan pemangku kepentingan di luar birokrasi.
Dengan nilai kontrak yang besar dan tenggat distribusi yang sempit, celah untuk praktik manipulasi harga (mark-up), kolusi, hingga suap menjadi sangat terbuka. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) milik KPK, sektor PBJ masih menjadi penyumbang terbesar dalam kasus suap dan gratifikasi. Dan dalam konteks MBG, pola ini kembali terulang—dengan masyarakat sipil dan satuan pendidikan tidak diberi ruang untuk mengawasi jalannya pengadaan maupun kualitas bahan pangan.
Ketika Gizi Menjadi Ancaman: Anak-anak Jadi Korban
Kekacauan tata kelola bukan hanya menghasilkan ketimpangan administratif. Ia juga menyentuh aspek yang lebih fundamental: kesehatan anak-anak. Dalam laporan TII, tercatat setidaknya satu kasus keracunan makanan yang dialami siswa akibat bahan pangan yang tidak layak konsumsi. Insiden ini menandakan bahwa persoalan tidak berhenti pada rendahnya kualitas bahan, tapi juga merembet ke distribusi yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan.
“Pengawasan yang longgar ibarat membuka pintu bagi bencana,” ujar seorang aktivis pendidikan yang dikutip dalam laporan tersebut.
Program yang seharusnya menjadi penyokong pertumbuhan generasi muda justru berbalik menjadi ancaman. Bukan karena niat buruk, tetapi karena sistem yang dibiarkan lemah dan mudah ditunggangi.
Beban Fiskal yang Melebihi Batas Aman
TII juga memperingatkan risiko fiskal yang mengintai. Karena tidak memiliki sistem prioritas penerima manfaat, MBG dianggap tidak efisien dan berpotensi mendorong defisit anggaran negara hingga 3,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB)—melampaui batas maksimum 3% yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara.
Dalam simulasi TII, potensi kerugian dari pelaksanaan MBG bisa mencapai Rp1,8 miliar per tahun di setiap titik layanan. Jika dikalkulasi secara nasional, kerugian tersebut dapat menembus puluhan triliun rupiah. Tanpa intervensi serius, program ini bukan hanya gagal menyehatkan, tetapi juga mengancam stabilitas keuangan negara.
Langkah Perbaikan: Selamatkan Sebelum Terlambat
Transparency International Indonesia tidak berhenti pada peringatan. Mereka mengajukan serangkaian rekomendasi yang bertujuan untuk menyelamatkan MBG dari kegagalan total. Langkah pertama yang disarankan adalah moratorium atau penghentian sementara seluruh pelaksanaan program, hingga Perpres sebagai dasar hukum resmi dikeluarkan. Tanpa regulasi yang jelas, pelaksanaan MBG akan terus berjalan dalam ruang abu-abu yang rawan diselewengkan.
Selanjutnya, pembenahan menyeluruh dalam proses seleksi mitra pelaksana dianggap sangat mendesak. TII menekankan pentingnya membuka proses ini kepada publik, memastikan bahwa yang terpilih adalah mereka yang memiliki rekam jejak profesional, bukan hubungan politis atau kedekatan institusional semata.
Distribusi bantuan, menurut TII, harus dilakukan secara lebih terarah dengan pendekatan berbasis kebutuhan. Prioritas harus diberikan kepada daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau, seperti wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan pendekatan ini, negara bisa memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
Aspek pengawasan juga harus diperluas. Tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan internal birokrasi. Masyarakat sipil, satuan pendidikan, dan komunitas lokal perlu dilibatkan secara aktif untuk memastikan kualitas makanan, keadilan distribusi, dan transparansi penggunaan anggaran. Selain itu, audit kinerja dan keuangan harus dilakukan secara berkala, dan yang terpenting—dipublikasikan secara terbuka. Audit tidak boleh menjadi laporan formalitas yang berhenti di meja birokrat, melainkan harus menjadi dasar koreksi kebijakan yang terus-menerus.
Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan sungguh-sungguh, program MBG bisa diselamatkan. Bukan hanya dari segi fiskal, tetapi juga dari kehilangan makna dan kepercayaan masyarakat.
Simbol Kepedulian yang Bisa Menjadi Luka Kolektif
Pada akhirnya, TII menutup laporannya dengan catatan penting: jika tidak segera diperbaiki secara struktural, program MBG bisa menjadi preseden buruk bagi masa depan kebijakan sosial di Indonesia. Ia bisa berubah dari simbol kepedulian negara menjadi arena baru korupsi yang menghancurkan integritas pemerintahan.
“Ini bukan hanya soal uang rakyat yang dikorupsi, Ini soal bagaimana negara kehilangan integritasnya saat menyentuh dapur rakyat," kutipan dari hasil riset TII.
Di antara piring-piring plastik di sekolah-sekolah, di antara nasi dan lauk pauk sederhana yang disajikan setiap siang, tersimpan sebuah pertaruhan besar: apakah negara benar-benar hadir untuk rakyatnya, atau sekadar menyajikan ilusi kesejahteraan yang penuh jebakan.(*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Laporan TII: Potensi Korupsi Rp400 Triliun di Ujung Sendok MBG
| Pewarta | : Ferry Agusta Satrio |
| Editor | : Imadudin Muhammad |